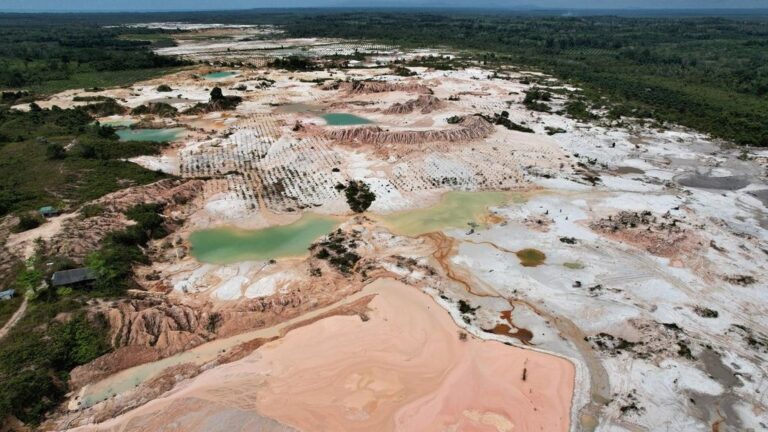“PERANG DAN PERDAMAIAN : MENGGALI AKAR KONFLIK ISRAEL – PALESTINA YANG TAK BERUJUNG’’
OLEH : ANGGA ARVEN FAJAR (DIVISI PENELITIAN DAN KAJIAN STRATEGIS PPIM 2024)
Tinjauan
Konflik Israel-Palestina telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade, bermula dari masa mandat Inggris setelah Perang Dunia I. Ketegangan meningkat dengan imigrasi besar-besaran Yahudi ke Palestina, didukung oleh Deklarasi Balfour 1917 yang menjanjikan tanah bagi bangsa Yahudi. Puncaknya terjadi pada 1948, ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, yang memicu perang dengan negara-negara Arab tetangga dan mengakibatkan ribuan warga Palestina kehilangan tempat tinggal. Konflik ini terus diperburuk oleh isu-isu utama seperti status Yerusalem, hak kembali pengungsi Palestina, pembangunan permukiman Yahudi di wilayah pendudukan, serta perjuangan untuk mendirikan negara Palestina.
Jalur Gaza, di bawah kendali Hamas sejak 2007, sering menjadi pusat eskalasi dengan blokade dan serangan militer yang memperburuk kondisi kemanusiaan. Meskipun berbagai upaya perdamaian, termasuk Perjanjian Oslo pada 1990-an, telah diupayakan, kebuntuan diplomatik, kekerasan, dan ketegangan politik terus menghalangi tercapainya solusi yang berkelanjutan. Konflik ini tetap menjadi tantangan global yang kompleks, memengaruhi stabilitas kawasan dan memicu dampak kemanusiaan yang signifikan.
Kontroversi Deklarasi Balfour
Melemahnya Kekaisaran Ottoman pada masa Perang Dunia I membuat wilayahnya jatuh ke tangan aliansi pemenang perang, termasuk Inggris, yang mendapat mandat untuk mengelola Palestina berdasarkan Perjanjian Sykes-Picot 1916. Palestina ditempatkan di bawah administrasi Inggris sebagai bagian dari British Zone, memberikan Inggris peluang untuk mengeluarkan Deklarasi Balfour pada 1917. Surat dari Arthur Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, kepada Lionel Walter Rothschild, tokoh Yahudi Inggris, menyatakan dukungan terhadap pendirian “rumah nasional bagi bangsa Yahudi” di Palestina. Namun, deklarasi ini mengabaikan hak-hak sosial dan historis penduduk Arab Palestina yang telah menghuni wilayah tersebut selama lebih dari 1.200 tahun. Pada saat itu, populasi Yahudi di Palestina masih di bawah 10%, tetapi Inggris aktif memfasilitasi imigrasi Yahudi besar-besaran ke wilayah tersebut, yang kemudian dianggap sebagai upaya mendirikan negara Yahudi (Nurdyawati, 2020).
Kontroversi Deklarasi Balfour terutama terletak pada interpretasi istilah “rumah nasional,” yang dianggap mencerminkan ambisi pendirian negara Yahudi, serta kebijakan Inggris yang cenderung memihak Yahudi. Kebijakan Inggris, seperti Passfield Reversal, memperkuat komitmen terhadap Deklarasi Balfour dan memperburuk hubungan dengan penduduk Palestina yang merasa diperlakukan tidak adil. Palestina memprotes kebijakan Inggris ini karena dianggap sebagai pemicu konflik dan ketegangan yang terus berlanjut. Selain itu, pembatasan terhadap pengembangan wilayah Palestina bertolak belakang dengan hak-hak yang diberikan Inggris kepada penduduk lokal di Suriah dan Irak, menandai awal ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Palestina hingga saat ini (Nurdyawati, 2020).
Imigrasi Yahudi ke Palestina
Konflik Israel-Palestina berakar dari perspektif teologis dan historis. Setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman pasca-Perang Dunia I, Palestina berada di bawah mandat Inggris berdasarkan Liga Bangsa-Bangsa, yang mengadopsi Deklarasi Balfour 1917. Deklarasi ini mendukung pembentukan negara Yahudi di Palestina, yang dianggap Zionis sebagai “tanah yang dijanjikan Tuhan” dalam Perjanjian Lama. Antara 1920-1929, sekitar 100.000 imigran Yahudi pindah ke Palestina, yang saat itu memiliki sekitar 750.000 penduduk Palestina. Setelah Holocaust, arus migrasi Yahudi ke Palestina meningkat tajam, dipimpin oleh organisasi Zionis yang mengatur tempat tinggal dan pekerjaan mereka. Pada 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya, mengusir ribuan warga Palestina dan menghancurkan lebih dari 400 desa dalam periode 1948-1949. Konflik terus berlangsung dengan pendudukan wilayah seperti Jalur Gaza dan Tepi Barat oleh Israel (Wirajaya,2020).
Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa ( PBB )
1. Resolusi 181 (1947)
Resolusi ini dikeluarkan pada akhir 1947, mengusulkan pembagian Palestina menjadi wilayah untuk bangsa Yahudi (55%) dan bangsa Arab (45%) dan menetapkan Yerusalem sebagai kota internasional di bawah pengelolaan PBB. Resolusi ini menjadi dasar untuk pembentukan negara Israel, meskipun ditolak oleh negara-negara Arab yang menentang pembagian wilayah tersebut.
2. Resolusi 194 (1948)
Resolusi ini dikeluarkan setelah Perang Arab-Israel 1948. Resolusi ini menetapkan hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka atau menerima kompensasi jika mereka memilih tidak kembali, serta mengusulkan internasionalisasi Yerusalem sebagai wilayah khusus di bawah pengawasan PBB. Resolusi ini sering dirujuk dalam diskusi tentang hak-hak pengungsi Palestina, meskipun implementasinya terbatas karena penolakan Israel terhadap banyak ketentuannya.
3. Resolusi 242 (1967)
Resolusi ini dikeluarkan setelah Perang Enam Hari 1967. Resolusi ini menuntut penarikan Israel dari wilayah yang diduduki selama perang, termasuk Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan, serta menekankan prinsip “tanah untuk perdamaian,” yang mengharuskan Israel mundur dari wilayah pendudukan dengan imbalan pengakuan dan perdamaian dari negara-negara Arab. Resolusi ini menjadi dasar bagi banyak proses perdamaian, termasuk Kesepakatan Oslo, meskipun interpretasinya sering diperdebatkan.
4. Resolusi 338 (1973)
Resolusi ini dikeluarkan selama Perang Yom Kippur 1973. Resolusi ini menyerukan penghentian segera pertempuran dan menegaskan kembali Resolusi 242 sebagai dasar untuk negosiasi damai di Timur Tengah. Resolusi ini memperkuat Resolusi 242 dan menjadi pijakan untuk pembicaraan damai antara Mesir, Israel, dan Suriah.
5. Resolusi 478 (1980)
Resolusi ini mengecam Israel karena mengadopsi undang-undang yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota yang “utuh dan bersatu” dan menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran hukum internasional. Resolusi ini juga meminta negara-negara anggota PBB untuk tidak menempatkan kedutaan besar mereka di Yerusalem. Resolusi ini mencerminkan ketegangan internasional terkait status Yerusalem, dengan sebagian besar negara mengikuti arahan ini hingga beberapa negara, seperti AS, memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.
6. Resolusi 2334 (2016)
Resolusi ini mengecam pembangunan permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan, termasuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur, serta menegaskan bahwa permukiman ini melanggar hukum internasional dan mengancam solusi dua negara. Resolusi ini mempertegas sikap internasional terhadap permukiman ilegal Israel, meskipun Israel menolak resolusi tersebut.
Semua resolusi ini menunjukkan upaya PBB dalam menangani konflik Israel-Palestina. Meskipun memiliki dampak signifikan dalam membentuk pandangan internasional, pelaksanaan resolusi-resolusi tersebut sering kali terkendala oleh dinamika politik dan kepentingan negara-negara yang terlibat, terutama dalam hal penerimaan oleh pihak yang terlibat langsung dalam konflik (Wirajaya,2020).
Konflik Terbentuknya Negara Israel
Konflik antara Palestina dan Israel bermula dari klaim atas tanah yang telah lama ditempati, dengan akar sejarah yang dalam. Bangsa Israel kuno mendirikan Kerajaan Israel pada 1000 SM di wilayah Palestina, namun setelah penjajahan, mereka bermigrasi ke Eropa dan Timur Tengah. Pada abad ke-19, Yahudi Eropa mulai membeli tanah di Palestina melalui Jewish National Fund, dan eksodus besar-besaran terjadi antara 1895-1914 untuk mendirikan koloni demi pembentukan negara Israel. Keberadaan mereka menimbulkan ketegangan dengan penduduk Arab Palestina yang khawatir akan kehilangan tanah. Ketegangan semakin meningkat setelah Deklarasi Balfour 1917 yang mendukung pendirian negara Yahudi di Palestina dan berlanjut dengan mandat Inggris di Palestina. Setelah Perang Dunia II dan krisis pengungsi Yahudi, PBB mengusulkan pembagian wilayah Palestina pada 1947, yang ditolak oleh negara-negara Arab dan Palestina, hingga Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948. Hal ini memicu invasi negara-negara Arab dan membuka babak baru konflik (Adhim & Yuliati, 2021).
Konflik besar antara Israel dan negara-negara Arab berlanjut melalui perang-perang besar seperti Perang Suez 1956, Perang Enam Hari 1967, dan Perang Yom Kippur 1973. Perang Enam Hari mengakibatkan Israel menguasai wilayah strategis seperti Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan. Meski perang berkepanjangan, berbagai upaya negosiasi dilakukan, termasuk Konferensi Jenewa 1973 dan Perjanjian Oslo 1993 yang memberikan Palestina yurisdiksi terbatas. Namun, ketegangan tetap berlanjut hingga hari ini, dengan akar konflik yang melibatkan aspek historis, politis, dan agama, dan meskipun ada kesepakatan, perdamaian yang permanen belum tercapai (Amal, 2020).
Perjanjian Perdamaian Oslo
Setelah proklamasi Negara Israel pada 14 Mei 1947 dan Negara Palestina pada 15 November 1988, konflik tetap berlanjut akibat perbedaan pandangan di kedua belah pihak. Di Palestina, terdapat tiga faksi utama: kelompok nasionalis seperti PLO dan Fatah yang mendukung perundingan damai tetapi menolak negara Islam; kelompok oposisi nasionalis kiri yang bersifat sosialis dan menolak perjanjian Oslo 1993; serta kelompok Hamas dan Jihad Islam yang menolak keberadaan Israel dan memperjuangkan negara Islam. Sementara itu, politik Israel terbagi antara kubu kiri yang moderat dan kubu kanan yang garis keras. Kubu kiri mendukung solusi damai tanpa kekuatan militer, sedangkan kubu kanan seperti Likud menolak konsesi pada Palestina, mendukung pemukiman Yahudi, dan memilih pendekatan militer. Konflik internal di masing-masing pihak turut memperumit upaya perdamaian (Badjodah& Ahmad, 2021).
Berbagai inisiatif perdamaian telah dilakukan, termasuk Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB tahun 1967 yang menyerukan dua prinsip utama, yaitu:
- penarikan pasukan Israel dari wilayah-wilayah yang diduduki sejak perang 1967
- penghormatan terhadap kedaulatan serta pengakuan hak hidup damai semua negara di kawasan tersebut.
Perjanjian Oslo (1993) adalah langkah penting dalam proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Dihasilkan dari pembicaraan rahasia yang diadakan di Oslo, Norwegia, perjanjian ini mengarah pada pengakuan resmi oleh Israel terhadap PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina, sementara PLO mengakui hak Israel untuk eksis.
Hasil-hasil utama dari Perjanjian Oslo adalah sebagai berikut:
1. Pembentukan Otoritas Palestina (PA)
Salah satu hasil utama dari perjanjian ini adalah pembentukan Otoritas Palestina (PA), yang diberi wewenang administratif di beberapa wilayah Palestina, terutama di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
2. Penarikan Bertahap Pasukan Israel
Sebagai bagian dari kesepakatan, Israel setuju untuk menarik pasukannya secara bertahap dari beberapa daerah yang sebelumnya diduduki, termasuk daerah-daerah di Tepi Barat dan Gaza.
3. Pemilu Palestina
Perjanjian Oslo juga mengatur pelaksanaan pemilu untuk memilih pemimpin-pemimpin Palestina yang akan memimpin Otoritas Palestina.
4. Pembahasan Status Final
Salah satu aspek yang lebih penting namun belum terselesaikan dari perjanjian ini adalah pembahasan mengenai “status final” yang mencakup beberapa isu utama, seperti:
- Yerusalem: Status Yerusalem, yang dianggap oleh kedua belah pihak sebagai ibu kota mereka, belum disepakati.
- Pemukiman Yahudi: Israel berkomitmen untuk membatasi pembangunan permukiman, namun tidak ada kesepakatan konkret mengenai penghentian total.
- Pengungsi Palestina: Nasib pengungsi Palestina yang diusir atau melarikan diri selama konflik tetap menjadi masalah yang belum terselesaikan.
Meskipun Perjanjian Oslo berhasil membuka jalur komunikasi dan beberapa langkah penting seperti pembentukan PA dan pemilu, implementasinya menemui hambatan besar. Konflik internal di Palestina antara faksi-faksi seperti Hamas dan Fatah, serta kelanjutan pembangunan pemukiman Yahudi oleh Israel, memperburuk situasi. Selain itu, ketegangan yang tidak terselesaikan mengenai status final dan kekerasan yang terus berlangsung mengarah pada Intifada Kedua pada 2000. Meskipun demikian, Perjanjian Oslo tetap dianggap sebagai tonggak sejarah dalam upaya perdamaian, meskipun perdamaian yang menyeluruh belum tercapai hingga saat ini.
Eskalasi Kekerasan
Intifada Kedua (2000–2005), atau Intifadhah al-Aqsha, dipicu oleh kunjungan kontroversial Ariel Sharon ke kompleks Masjid Al-Aqsa, yang memprovokasi demonstrasi besar-besaran dan respons keras dari militer Israel. Perlawanan ini mencerminkan frustrasi rakyat Palestina terhadap pendudukan yang terus berlanjut serta pelanggaran terhadap Perjanjian Oslo. Konflik ini mengakibatkan korban jiwa yang sangat besar, dengan lebih dari 4.000 warga Palestina dan lebih dari 1.000 warga Israel tewas. Intifada ini menjadi simbol perjuangan Palestina melawan represi, memperkuat tekad rakyat Palestina untuk melawan dominasi Israel (Sari, 2022).
Pada 2007, konflik internal Palestina semakin rumit dengan pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas melalui kudeta terhadap Otoritas Palestina. Perpecahan antara Hamas di Gaza dan Fatah di Tepi Barat memperburuk situasi, memperdalam krisis politik dan kemanusiaan. Blokade ketat oleh Israel dan Mesir terhadap Gaza memperparah kondisi kehidupan di wilayah tersebut. Dari perspektif konstruktivisme, konflik ini tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika politik internal, tetapi juga oleh konstruksi sosial yang melibatkan aktor eksternal seperti Amerika Serikat, yang melalui kebijakan gradualisme dan dukungan terhadap Israel, dianggap memperpanjang ketegangan melalui lingkaran sebab-akibat (Sari, 2022).
Serangan Hamas dan Balasan Israel
Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang dikenal sebagai “Operasi Taufan Al Aqsa,” memicu respons militer besar-besaran dari Israel terhadap Jalur Gaza. Konflik ini menyebabkan lebih dari 45.000 korban jiwa, termasuk ribuan anak-anak, serta menciptakan krisis kemanusiaan dengan jutaan pengungsi yang kehilangan tempat tinggal. Blokade ketat Israel terhadap makanan, bahan bakar, dan air semakin memperburuk situasi, yang oleh Human Rights Watch dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa Keempat (Al Farauqi & Mariana, 2024).
Selain itu, respons militer Israel ditandai dengan dugaan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI), seperti serangan terhadap warga sipil dan penggunaan senjata berbahaya seperti fosfor putih. Serangan ini menghancurkan fasilitas publik, termasuk rumah sakit dan sekolah, serta menghalangi bantuan kemanusiaan. Tindakan ini melanggar prinsip-prinsip HHI, seperti pembedaan dan proporsionalitas, sehingga mendorong desakan untuk intervensi internasional yang lebih tegas demi melindungi penduduk sipil Gaza (Al Farauqi & Mariana, 2024).
Hambatan Perdamaian dan Pelanggaran Hukum Internasional
Penyelesaian konflik Palestina-Israel telah diupayakan melalui perang, diplomasi bilateral, dan multilateral. Beberapa perjanjian penting seperti Perjanjian Camp David (1978), Oslo I (1993), Oslo II (1994), dan Peta Jalan Damai (2002) bertujuan menciptakan negara Palestina merdeka. Upaya regional juga dilakukan, termasuk Proposal Damai Arab pada KTT Liga Arab 2005, yang meminta Israel mundur dari wilayah pendudukan sejak 1967 dan mendukung solusi bagi pengungsi Palestina. Namun, berbagai inisiatif ini terhambat oleh sikap Israel dan kebijakan Amerika Serikat yang pro-Israel, seperti kebijakan veto di PBB terhadap resolusi yang mengkritik Israel, termasuk Resolusi DK PBB No. 242 (1967) dan Resolusi 1860 (2009). Dominasi veto AS dan pendekatan Israel yang agresif telah memperumit peluang untuk menyelesaikan konflik (Firdaus & Yani, 2020).
Selain hambatan diplomasi, konflik ini juga ditandai oleh pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI). Israel dinilai melanggar prinsip pembedaan dan proporsionalitas, termasuk penggunaan bom fosfor putih yang menyebabkan kerusakan parah pada manusia dan lingkungan, melanggar Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977. Serangan terhadap masyarakat sipil, fasilitas publik, dan tenaga medis juga bertentangan dengan Konvensi Jenewa IV 1949. Selain itu, Israel dilaporkan menyiksa tawanan Palestina dan memblokir bantuan kemanusiaan, melanggar Konvensi Jenewa III dan IV. Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan kegagalan untuk mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan dalam konflik bersenjata, yang semakin memperburuk situasi di wilayah konflik (Pratiwi, 2024).
Peran Diplomasi indonesia dalam Konflik Israel- Palestina
Indonesia secara konsisten berada di garis depan dalam mendukung hak-hak Palestina, sesuai dengan cita-cita Pembukaan UUD 1945 yang menolak kolonialisme dalam segala bentuk. Hubungan erat antara Indonesia dan Palestina telah terjalin sejak sebelum kemerdekaan, di mana Palestina menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Melalui politik luar negeri bebas aktif, Indonesia menolak kolonialisme dan mendukung kemerdekaan Palestina. Sebagai anggota tidak tetap DK PBB (2007-2008), Indonesia aktif memperjuangkan hak Palestina dengan mendorong sidang khusus Dewan HAM dan Majelis Umum PBB. Indonesia juga menjadi co-sponsor pengakuan Palestina sebagai negara pemantau non-anggota PBB pada 2012 dan pengibaran bendera Palestina di Markas Besar PBB (Nurhasanah & Debi Setiawati, 2024).
Selain itu, Indonesia telah menjadi tuan rumah berbagai konferensi internasional terkait Palestina, seperti Konferensi Asia Afrika dan KTT Luar Biasa OKI, serta mengecam langkah Israel yang melanggar hukum internasional, termasuk pembangunan permukiman ilegal dan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Bantuan konkret Indonesia mencakup pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, pelatihan bagi warga Palestina, dan kontribusi aktif pada UNRWA. Sikap tegas Indonesia mendukung solusi dua negara berdasarkan hukum internasional dan HAM terus diperjuangkan melalui diplomasi aktif dan berbagai forum internasional (Nurhasanah & Debi Setiawati, 2024).
Sumber
- Wirajaya, A.C. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA PALESTINA DAN ISRAEL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDY KASUS PERAMPASAN WILAYAH PALESTINA DI ISRAEL). LEX ET SOCIETATIS.
https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30909
- Firdaus, A.Y., & Yani, Y.M. (2020). FAKTOR PENGHAMBAT PERDAMAIAN KONFLIK PALESTINA – ISRAEL. Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora.
https://doi.org/10.47313/pjsh.v5i1.824
- Nurdyawati, T.T. (2020). Western Interest dalam Proses Perkembangan Negara Israel (1917-1948) Sebagai Akar Utama Konflik Israel-Palestina.
https://doi.org/10.19109/ampera.v1i1.5204
- Nurhasanah, R., & Debi Setiawati, S.M. (2024). Keterlibatan Indonesia Dalam Proses Perdamaian Konflik Palestina-Israel. Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial.
https://doi.org/10.59672/nirwasita.v5i1.3530
- Amal, I. (2020). The Future of Israel – Palestinian Conflict: Either One State or Two?
- Sari, A.T. (2022). Konflik Palestina-Israel Pada Masa Intifada II dalam Perspektif Konstruktivisme dan Strategi Politik. Jurnal ICMES.
https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v6i1.120
- Adhim, S., & Yuliati, Y.N. (2021). Konflik Terbentuknya Negara Israel pada Tahun 1948-1973. ASANKA: Journal of Social Science And Education.
https://doi.org/10.21154/asanka.v2i1.2429
- Badjodah, A.F., Husen, M., & Ahmad, S. (2021). DINAMIKA KONFLIK DAN UPAYA KONSENSUS PALESTINA-ISRAEL (Studi Kasus Perjanjian Perdamaian Oslo (Oslo Agreement ) Tahun 1993). Jurnal Cakrawala Ilmiah.
https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.619
- Pratiwi, N.R. (2024). Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel ke Palestina. Jurnal Hukum Indonesia.
https://doi.org/10.58344/jhi.v3i2.721
- Al Farauqi, M.D., & Mariana, M. (2024). Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel ke Gaza Pasca-Serangan Hamas 7 Oktober 2023. Jurnal ICMES.