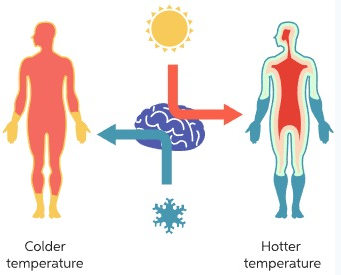Merenungi Kondisi Pendidikan Kita
Oleh : Mansurni Abadi, Anggota DITLIKA PPI DUNIA

Rasa-rasanya kita sepakat, tidak ada kekuataan lain di dunia yang mampu membebaskan manusia, baik secara individual maupun kolektif dari pembodohan, penindasan, penyimpangan, apalagi pemiskinan secara struktural maupun kultural jika tidak melalui proses pendidikan.
Kita boleh saja punya orang dalam yang kuat, mertua yang kaya, atau pun yayang yang 1 x 24 siap mendukung sat set set kita namun, tanpa proses pendidikan sirnalah semua itu. Disini yang saya maksudkan pendidikan bukan sebatas proses sekolah non-formal tapi laku yang terus menerus aktif mencari, mendalami, meng-internalisasi, dan kemudian menerapkan pengetahuan bukan sebatas bagi dirinya sendiri namun juga orang lain.
Kalau kata Fransisco Ferrer, sang anarkis Spanyol itu pendidikan akan selalu memberikan manusia kemampuan untuk memecahkan masalah, sedangkan masalah itu sendiri merupakan elemen yang akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Dengan pendidikan, maka manusia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di hidupnya. Oleh karena itu, pendidikan itu bukanlah suatu kepentingan lagi, tetapi kebutuhan dan keharusan.
Ketika saya berdikusi dengan kalangan aktivis literasi dari Sarawak, sehari sebelum hari raya tiba, salah seorang peserta menanyakan kepada saya mengapa kemiskinan itu berhubungan erat dengan pendidikan rendah dan kebodohan? Lalu saya menjawab, karena taraf berpikirnya masih terkungkung dalam masalah kesulitan ekonomi. Maka dari itu program pengentasan kemiskinan salah satunya juga berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan dan meningkatkan derajat berpikir masyarakat.
Terkadang terbersit sebuah pemikiran “Jika masyarakat miskin itu meningkatkan derajat ekonominya dan menjadi makmur, maka derajat berpikir mereka juga akan meningkat”. Benar atau salahnya teori ini bisa kita uji coba namun yang pasti pendidikan adalah kekuatan utama untuk merubah suatu bangsa.
Nah, berhubung pada tanggal 2 Mei yang lalu, kita baru saja merayakan hari pendidikan nasional. penting bagi kita untuk merefleksikan kembali kondisi pendidikan kita saat ini, biar telat asalkan ada coretan tentang itu. bukankah sudah tugas kaum terpelajar untuk selalu menyebarkan ide-ide, perkara ide itu dibaca atau tidak saya kira itu perkara nanti.
Disini maksud terpelajar perlu saya tegaskanjuga,bukanlah orang yang terus-menerus duduk di bangku sekolah karena saya sadar akses pendidikan formal masihlah sebuah keistimewaan di negeri yang rakyat-nya dinasehatkan untuk merebus ini, buat saya terpelajar itu adalah orang- orang yang mau belajar, baik teori maupun praktek serta peduli dengan masalah yang ada.
Salah satu tindakan yang mungkin di lakukan kaum terpelajar itu adalah melakukan refleksi,karena mau bagaimana lagi ? Ingin merubah kebijakan, belum ada jabatan apalagi ingin memberontak, nanti malah di tawari semangkok bakso. Bahkan sekadar mengkritik di status medsos saja, bisa berujung dihakimi buzzer.
Jadi ber-refleksi itu penting untuk untuk mengenali solusi, merasakan permasalahan, dan memaksa kita masuk ke dunia Dunia “what if?” yang identik dengan imajinasi yang menjadi ciri dari kemanusiaan kita sembari menghabiskan kopi di balkon rumah susun. Lalu apa sajakah masalah pendidikan yang patut kita renungi bersama untuk hari ini dan nanti.
A. Biaya pendidikan yang mahal
Dulu saat saya menjadi berkerja untuk yayasan Drug Free World Indonesia pada tahun 2018, yang tugasnya mengedukasi anak-anak muda untuk tidak memakai narkoba, pemukiman kumuh di beberapa kota di pulau jawa menjadi tempat yang harus kami kunjungi bersama BNN, saat berkunjung kesana, saya masih teringat dengan kata- kata para anak-anak remaja disana yang memilih untuk tidak bersekolah karena buat mereka sekolah itu hanyalah menambah beban orang tuanya yang sudah susah. Bagi sebagian dari mereka meninggalkan bangku sekolah adalah bentuk keprihatinan terhadap orang tua dan bagi sebagian lainnya dengan tidak bersekolah mereka dapat membantu ekonomi keluarganya.
Orang tua mereka sendiri tidak mampu berbuat banyak untuk mendorong anak bersekolah, disatu sisi mereka ingin anak mereka menjadi orang pintar namun disisi lain mereka pun harus memaklumi keadaan dan meng-iya-kan jalan yang dipilih anaknya. Tapi memang ada juga orang tua dari kalangan tidak mampu mendorong agar anaknya terus bersekolah tapi ironisnya banyak dari anak-anak itu yang harus berkerja ekstra sepulang sekolah karena orang tua mereka tidak memiliki biaya yang cukup untuk operasional sehari-hari.
Cobalah anda tinggal di wilayah-wilayah miskin di seantero negeri, tidak harus di kota bahkan di kota kecil sekalipun akan ada anak-anak dan remaja yang pulang sekolah untuk kembali keluar lagi mencari tambahan rezeki bahkan tidak sedikit dari mereka yang pulang hingga larut malam.
Saya merasa muak jika ada yang meromantisasi ini atas nama kedisplinan dan kerja keras, bagi saya anak-anak dan remaja yang tengah menempuh pendidikan dari keluarga kurang mampu itu tidaklah layak harus peras keringat sepulangnya bersekolah apalagi karena pekerjaan yang mereka lakukan mengharuskan mereka pulang hingga larut malam. Negara harus menjamin kebutuhan pembelajaran mereka, baik dari segi fasilitas, beasiswa per-semester, hingga uang saku agar mereka fokus pada pembelajaran saja.
Singkat cerita, kemudian saya dipertemukan dengan buku bagus berjudul “Orang Miskin Dilarang Sekolah”, geli sekaligus ironis dengan judulnya, tapi buat saya buku bergenre aktivisme dengan gaya penulisan asik yang itu sesuai dengan kondisi pendidikan indonesia yang sampai hari ini bahkan di kemudian hari nanti masih akan terus menerus mengkomoditaskan pendidikan sebagai sesuatu yang ekslusif.
Jika ada istilah pendidikan itu adalah barang mewah sebenarnya masihlah relevan meskipun bantuan sosial untuk pendidikan keluarga kurang mampu sedang digiat-giatkan oleh pemerintah namun perlu juga kita ingat kalau bantuan sosial yang sporadic dan angin-anginan hanya akan membuat peluang dan kesempatan untuk terjadi penyelewengan semakin besar.
Apalagi di tengah budaya yang kuat intervensi “Orang dalamnya”, bantuan pendidikan akhirnya menjadi komodi kepentingan, tidak jarang bantuan pendidikan untuk keluarga kurang mampu, misalnya, jatuh ditangan penerima yang tidak tepat.Faktor kedekatan dengan aparat, baik ditingkat desa hingga kota/kabupaten bahkan seringkali menjadi penentu untuk mendapatkan bantuan sosial,baik itu pendidikan ataupun lainnya.
Tepat tiga tahun lalu, ketika berdiskusi seputar pendidikan di asia tenggara bersama para peneliti di ISEAS Yusoff Ishak Singapura, ada kesimpulan menarik yang masih saya ingat sampai hari dari Dr. Kishore Mahbubani, penulis buku Has China Won ? Yang kemudian terkenal karena pujiannya dengan Jokowi itu menegaskan ada masalah mendasar yang menghalangi kemajuan indonesia, yang pertama karena rendahnya investasi di sektor pendidikan dan yang kedua, korupsi yang sudah membudaya.
Maka wajar saja kalau Indonesia pada tahun 2022 masih menempati urutan bawah di indeks pembangunan manusia atau HDI (Human Development Index)(Statistica, 2021). Menurut Suharso monoarfa (2021), faktor pendidikan menjadi penyebab utamanya. Oleh karena Indonesia harus segera meningkatkan pembelajaran yang menekankan pada keterampilan abad ke-21 yang berorientasi global dan meningkatkan sistem layanan pendidikan (akses) angka harapan lama sekolah.
Biaya pendidikan yang mahal memang akan mengakibatkan semakin jauhnya layanan pendidikan (yang bermutu) dari jangkauan kaum miskin. Dampaknya jelas, akan menciptakan kelas-kelas sosial dan ketidakadilan sosial. Padahal UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.
Kondisi yang demikian berakibat pada kemampuan kaum miskin (yang sebenarnya mereka pun tidak mau menjadi orang miskin) untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaannya sebagai manusia yang bermartabat menjadi sangat berat. Situasi ini menjadi semakin parah karena penilaian terhadap kemampuan intelektual subjek didik pun sangat ‘capital oriented’. Artinya akan nada bineritas yang saling bertolak belakang antara ilmu yang menguntungkan di pasaran dengan ilmu-ilmu yang tidak mendatangkan cuan.
B. Kesejahteraan guru yang dipermainkan
Drama hidup manusia itu hanya terdiri dari dua kondisi saja, kalau tidak tragedi, ya komedi. Dalam sejarah Yunani kuno, rumusan drama tragedi ini ditulis Aeschylos, Euripides, Sophocles. Sedangkan komedi, ditulis Aristhopanes. Tapi, dalam konteks Indonesia antara drama dan komedi itu kondisinya diciptakan oleh sistem dan para pemegang kebijakan. untuk urusan kesejahteraan guru misalnya, masih ada cerita-cerita yang bukan hoax tentang gaji guru yang hanya dibayar dibawah 500.000.
Memang tidak ada big data yang menyatakan berapa banyak guru yang bergaji rendah tapi kita selalu diperlihatkan kisah-kisah para guru yang digaji rendah ironisnya ada sebagian kalangan didalam pemerintahan kita yang kemudian meromantisasi gaji rendah para guru-guru itu dengan cap pengabdian padahal yang mereka lakukan bukan hanya semata-mata mengabdi tapi juga mencari nafkah untuk keluarganya.
Secara pribadi, saya banyak memiliki kawan yang berstatus guru honorer maupun guru kontrak di sekolah swasta yang digaji dengan amat sangat rendah namun diberikan beban kerja yang banyak.
Mungkin ada yang membaca artikel ini pun memiliki kenalan, baik kawan maupun keluarga yang menjadi tenaga pengajar yang hanya diperas tenaga dan pikiran tanpa mendapatkan upah yang setimpal atau anda sendiri adalah tenaga pengajar itu, saya sangat prihatin sekaligus bersolidaritas terhadap kawan-kawan pengajar yang digaji dengan nominal yang main-main untuk pekerjaan yang akan menentukan generasi bangsa bahkan disela-sela waktu mengajar mereka, mau tidak mau harus membuat usaha sampingan demi memenuhi tuntutan hidup.
Sebenarnya jika memang ingin pendidikan maju, dan di antara caranya adalah mensejahterakan guru dan memenuhi kebutuhan pelajaran siswa, ini tentu menjadi pertanyaan kritis, mengapa tidak diberikan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan? Hal ini tentu berkaitan dengan anggaran yang dimiliki pemerintah. Kebutuhan negara selain pendidikan itu banyak, ada pertahanan, kesehatan, dll.
Kalau anggaran pendidikan ditambah, konsekuensinya ada anggaran bidang lain yang dikurangi.Lalu pertanyaannya menjadi, apa dasar bagi perubahan anggaran itu? Mana yang mesti dikurangi? Apakah aturan tata negaranya memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan anggaran ke sektor strategis lainnya seperti pendidikan ? Ah, saya rasa biarlah jin di pohon pisang yang akan menjawabnya. Pada point ini saya sematkan puisi yang tentang para pembawa cahaya pengetahuan yang nasibnya diabaikan.
Abdi kalian dipermainkan
Diromankan atas nama pengabdian
Katanya kita mau berjaya
Tapi yang mencerdaskan
Malah dilindas para tiran
Gaji murah diwajarkan
Fasilitas rusak didiamkan
Akses yang sulit di banggakan
Kata ingin kejayaaan
Tapi mereka disajikan kehampaaan.
Dapur mereka gelap gulita
Kelok kanan janji manis
Kelok kiri jurang aturan
Sampai kapan nasib ini
Tak bisa lagi mereka lukiskan
Tak sanggup lagi mereka tangisi
Sejahtera oase dipelupuk mata
Karena usia tak lagi mundur
Namun ada semakin kabur
C. Keterlepasan dari pendidikan karakter
Dulu saat di sekolah dasar saya dan mungkin juga anda pernah dipaksa berkompetisi. Ironisnya ,Segala cara dilakukan oleh orang tua yang ambisius agar anaknya menjadi ranking 1. Suap guru, gratifikasi, masukin les privat, bimbel dan sebagainya demi ranking 1. Orientasinya adalah hasil. Orientasi pada hasil ini mengabaikan pada proses yang tertib, disiplin, juga bertahap.
Kegandrungan pada hasil sangat tampak pada dicukupkannya murid-murid membaca satu buku untuk suatu subjek pelajaran atau malah satu buku lembaran soal yang disebut LKS (lembar kerja siswa). Dengan begitu mereka hanya diajar berpikir induktif, bukan deduktif atau komparatif.
Memang sekolah pada masa ini sebenarnya adalah pabrik, adalah candu masyarakat. Karena berorientasi pada hasil maka narsisisme, hedonisme, egoisme adalah kepercayaan dan prinsip. Segala yang abstrak berupa nilai etik, karakter, menjadi terlupa dan tidak penting untuk jadi acuan.
Presiden kita yang terhormat nan merakyat memang memiliki formula revolusi mental yang kalau dihubungkan dengan pemikiran bung karno ada tiga elemen yang seharusnya ada pada revolusi yaitu integritas, budaya kerja, dan gotong royong kalau secara jargon memang ketiga-tiga seringkali di kampanyekan namun, yang menjadi pertanyaan kritis, sudah sejauh mana penerapan revolusi mental ? Jika memang sudah diterapkan, apa indikator keberhasilannya? Jika tidak, apa rintangannya ?
Toh, pada akhirnya memang harus kita akui revolusi mental hanya sebatas jargon, karena memang pilihan pembangunan pada akhirnya lebih ke revolusi fisik. Menjelang akhir pemerintahannya, kita malah sering dipertemukan dengan kisah-kisah tentang manusia indonesia dengan mentalitas menerabas bahkan di lingkaran kekuasaannya sendiri. Karena suka menerabas maka bergentayanganlah manusia-manusia rapuh. Tidak punya kuda-kuda kuat. Sekali toel langsung belok. Sekali dikasih jabatan langsung jadi perompak.
Akhirul kalam, demikianlah refleksi yang saya tulis ditengah hiruk pikuk chow kit dengan suara “Ting” korek dari bapak-bapak yang selalu bergosip berteman kepulan asap surya dan ibu-ibu yang kesana kemari menjajakan makanan khas Indonesia. Sebenarnya refleksi seperti ini tidaklah terlalu banyak berguna, jangankan merubah bahkan mengugah saja belum tentu tapi setidaknya apa yang kita pikirkan perlu kita tuangkan untuk membuktikan eksistensi kita di dunia yang fana ini sekaligus memberikan pemantik untuk berpikir terhadap masalah-masalah bangsa tentu bagi mereka yang mau meluangkan untuk membacanya.